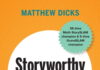Bulan lalu, OZIPmates sudah berkenalan dengan Nadia Murad, seorang aktivis kemanusiaan Yazidi asal Irak yang menerima penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2018. Bersama dengan dokter ahli penyakit wanita asal Kongo Denis Mukwege, Nadia menerima penghargaan tersebut untuk “usaha dalam mengakhiri penggunaan kejahatan seksual sebagai senjata perang”.
Namun kisah hidup Nadia jauh dari menyenangkan; sebelum ia menerima penghargaan Nobel, ia merupakan seorang penyintas dari genosida terhadap pemeluk agama Yazidi oleh ISIS pada tahun 2014 di desa asalnya di Kocho, Irak. Tidak hanya itu, ia juga dijadikan budak, diperjualbelikan, dan diperlakukan secara tidak manusiawi selama kurang lebih tiga bulan di kota Mosul, Irak sebelum ia melarikan diri ke Duhok di wilayah Kurdistan, Irak.
Kisah Nadia sebelum, saat, dan setelah ia diculik oleh ISIS diceritakan secara terperinci dalam buku autobiografi The Last Girl yang ditulis oleh Nadia bersama Jenna Krajeski, seorang wartawan asal Amerika.
The Last Girl terbagi menjadi tiga bagian: bagian pertama menceritakan kehidupan Nadia di Kocho bersama keluarganya serta genosida ISIS terhadap penduduk Kocho, bagian dua menceritakan kehidupannya sebagai budak ISIS, dan bagian tiga menceritakan bagaimana Nadia mampu melarikan diri dan menjadi aktivis kemanusiaan bagi kaum Yazidi.
Bagian pertama membuka sisi Nadia yang polos sebelum genosida terjadi. Nadia merupakan anak bungsu dari sebelas bersaudara. Meskipun tergolong keluarga miskin, Nadia mampu menjalani hidup dengan bahagia bersama saudara-saudaranya. Dalam bagian ini Nadia juga menceritakan kehidupannya sebagai orang Yazidi dan tradisi yang diikuti oleh pemeluk agama tersebut. Penulisan yang terperinci dipadu dengan bahasa yang mudah dimengerti membuat sudut pandang Nadia mampu menarik simpati pembaca, terutama terhadap warga Yazidi di Kocho yang menjadi korban genosida di akhir bagian pertama.
Bagian kedua adalah bagian yang paling menyakitkan: setelah genosida di desa Kocho, Nadia dijadikan budak seks oleh ISIS, diperjualbelikan layaknya barang dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Kejahatan seksual dialami oleh Nadia hampir setiap hari, dan di bagian ini jugalah Nadia mengutarakan ketidaksukaannya terhadap warga non-ISIS di Mosul yang membiarkan kekejaman terhadap dirinya—dan ribuan gadis Yazidi lain—terjadi. Tidak bisa dipungkiri bahwa bagian kedua adalah bagian yang dipenuhi oleh topik sensitif, dan lagi-lagi penulisan The Last Girl mampu membawakan kisah Nadia dengan dewasa tanpa menghilangkan makna dari pengalaman pahit yang dialami olehnya.
Bagian ketiga tidak hanya menceritakan bagaimana Nadia berhasil melarikan diri dari ISIS, tapi juga bagaimana ia bertemu dengan sisa-sisa keluarganya di Duhok dan bagaimana mereka berusaha pulih dari peristiwa menyakitkan yang mereka alami di Kocho. Kisah kaburnya Nadia dari ISIS penuh dengan intrik; ia dibantu oleh sebuah keluarga di Mosul yang membuka pintu untuknya dan menyelundupkannya melewati pos perbatasan ISIS dengan identitas palsu. Meskipun begitu, perjuangan Nadia masih jauh dari selesai; ia harus berdamai dengan kenyataan bahwa rumahnya telah diambil dan banyak dari keluarga dan teman-temannya telah hilang. Di sinilah ia menemukan tekadnya untuk mengadvokasi kaum Yazidi di dunia dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas usaha penghapusan kaum Yazidi dari muka bumi.
The Last Girl bukanlah sebuah buku yang mudah dibaca. Namun bila OZIPmates bisa bertahan sampai akhir, OZIPmates akan menemukan kisah luar biasa dari seorang wanita berani yang mampu berdiri setelah dirinya diperlakukan secara rendah. Bagaimanapun juga, judul The Last Girl tidak berarti Nadia sebagai salah satu gadis terakhir dari kaum Yazidi—tapi harapannya menjadi gadis terakhir yang harus melalui pengalaman pahit seperti kisahnya.
Teks: Jason Ngagianto
Foto: Penguin Random House