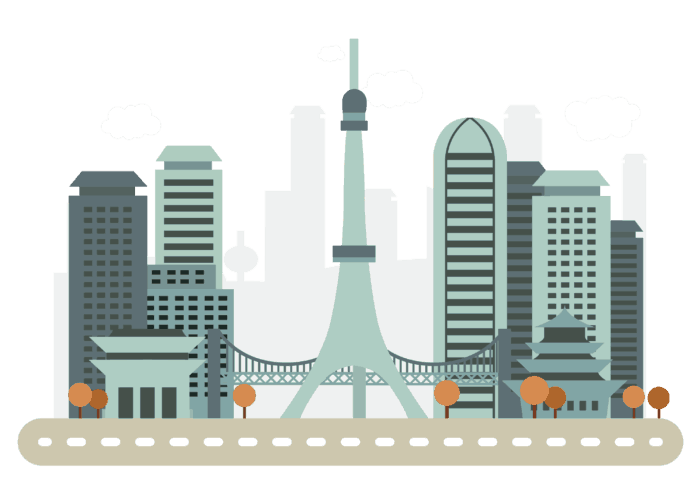Kesan pertama ketika kita bertemu dengan orang Jepang, terutama di Jepang, adalah: betapa sopan dan santunnya mereka!
Ketika kita berbicara, kalau mungkin, jangan terlalu angkat suara, jangan hingar-bingar, hingga mengganggu orang lain di sekitar kita.
Perkataan “arigato” (terima kasih) begitu sering menghiasi bibir orang Jepang; kebiasaan membungkuk merupakan bagian dari “halo apa kabar?” dan “sampai nanti, ya?”
Rakyat Jepang sudah terbiasa sopan, tertib, disiplin, hormat, halus, kasarnya: tidak perlu diatur, mereka lebih cenderung mengatur diri sendiri. Dan senantiasa, umumnya, mempertimbangkan kepentingan dan kenyamanan orang lain.
Ketika saya dan isteri berjalan-jalan di ibukota Tokyo, maka yang paling mengesankan adalah kebersihan kota tersebut, meski di awal musim dingin ketika pepohonan yang menghiasi hampir semua kedua sisi jalan di kota tersebut, sejak musim gugur, sudah melepaskan dedaunan mereka dari ranting dan dahannya, dan terus melakukannya sampai awal musin dingin, sebelum akhirnya memang rontok semua. Namun tetap saja terlihat kebersihan dan kerapihan.
Pelalu-lalang (pedestrian) begitu sadar akan adanya pelalu-lalang lainnya, hingga mereka benar-benar mengambil jalan yang paling minimal akan terjadi benturan, meski terlihat mereka berjalan dengan bergegas.
Kemudian lalu lintas yang juga tertib, yang jarang-jarang membunyikan klakson mereka.
Kendaraan-kendaraan di Tokyo (dan tentunya bagian-bagian lain Jepang) begitu patuh pada peraturan lalu lintas, hingga di persimpangan-persimpangan yang tidak ada lampu jalannya, setiap kendaraan niscaya akan berhenti atau melarikan kendaraan dengan sangat perlahan ketika menghampiri tempat penyeberangan, biar pun ketika itu tidak ada pedestrian yang hendak melintas.
Dan ketika kita akan menyeberangi jalan di bagian-bagian penuh keramaian di ibukota Jepang itu, maka niscaya kita akan dihibur oleh rekaman kicauan burung, yang menandakan hak pedestrian untuk menyeberang.
Dan hampir tidak ada terlihat mobil yang kotor yang melintasi jalan-jalan yang rapih-rapih itu.
Tapi jangan terkejut kalau anda ternyata tidak bisa membuang sampah di tempat umum, karena memang jarang-jarang ada tong sampah umum di kota ini. Ibaratnya, anda menghasilkan sampah, maka tanggungjawab anda membawa sampah itu pulang.
 Kaki lima jalan-jalan yang sangat lebar di bagian-bagian elit kota Tokyo dihiasi gambar dengan pesan yang dipahami masyarakat internasional, meski tulisannya dalam huruf kanji: DILARANG MEROKOK. Tidak boleh merusak paru-paru di jalan umum, meski banyak restoran dan tempat-tempat minum, yang terlihat membolehkan perokok menikmati kecanduan mereka itu. (Kebetulan rokok adalah di antara segelintir barang yang harganya sangat murah dibanding dengan di Australia, sekitar 400 yen satu paket 20 batang; barang-barang lainnya memang relatif sangat mahal).
Kaki lima jalan-jalan yang sangat lebar di bagian-bagian elit kota Tokyo dihiasi gambar dengan pesan yang dipahami masyarakat internasional, meski tulisannya dalam huruf kanji: DILARANG MEROKOK. Tidak boleh merusak paru-paru di jalan umum, meski banyak restoran dan tempat-tempat minum, yang terlihat membolehkan perokok menikmati kecanduan mereka itu. (Kebetulan rokok adalah di antara segelintir barang yang harganya sangat murah dibanding dengan di Australia, sekitar 400 yen satu paket 20 batang; barang-barang lainnya memang relatif sangat mahal).
Sewaktu kami berada di Jepang, sekitar awal Desember, menjelang Natal, begitu banyak pepohonan di sisi-sisi jalan yang dihiasi oleh bola-bola lampu kecil-kecil, yang dengan sangat telaten dipasang di ranting-ranting pohon yang ketika malam tiba, sekitar pukul 16:30 waktu setempat, bersinar dengan megahnya bak bintang-bintang di langit. Apalagi lampu-lampu kristal yang tambah menyemarakkan suasana di negara yang mayoritas rakyatnya menganut ajaran Shinto dan Buddha. Hanya antara 1 s/d 3% yang menganut ajaran Kristiani, namun semarak menjelang Natal terkesan lebih meriah di Tokyo dibanding banyak kota-kota besar lainnya di Barat.
Jepang memang “kaya” aliran listrik yang dibangkitkan dengan tenaga nuklir (meski demikian ternyata hanya kota Las Vegas, Amerika Serikat, satu-satunya yang dapat terlihat dari antariksa, karena gemerlap lampu-lampu kota judi tersebut).
Tokio memang indah, meski tidak seindah London atau Roma atau Wina atau Paris.
Kenapa?
 Karena umumnya bangunan di Tokyo bercirikan modernitas – jarang-jarang terlihat bangunan-bangunan tua khas arsitektur Jepang, seperti bangunan-bangunan “kuno” khas peninggalan zaman klasik, yang terlihat menghiasi kota-kota di Eropah itu.
Karena umumnya bangunan di Tokyo bercirikan modernitas – jarang-jarang terlihat bangunan-bangunan tua khas arsitektur Jepang, seperti bangunan-bangunan “kuno” khas peninggalan zaman klasik, yang terlihat menghiasi kota-kota di Eropah itu.
Akan tetapi patut diingatkan kembali bahwa Jepang adalah negara yang paling babak belur dalam Perang Dunia II (Perang Pasifik). Hanya Jepang-lah yang pernah mengalami serangan bom atom (Hiroshima dan Nagasaki – masing-masing tanggal 6 dan 9 Agustus 1945). Mungkin saja Jepang boleh bangga karena menjadi sasaran bom atom/nuklir, sementara Jerman yang juga kalah dalam Perang Dunia II tidak sampai diatomi, meski kota Dresden, Jerman, sempat luluh lantak, namun hanya oleh bom biasa.
Kenyataan bahwa Jepang sempat merasakan dahsyatnya hantaman bom atom, patut, di sisi lain, membanggakan negara dan bangsa ini, karena meski sempat porak poranda, Jepang, sebagaimana halnya Jerman, ternyata mampu membangun kembali dengan begitu gegap gempitanya.
Bukan itu saja, melainkan juga akan halnya Jepang bahkan sanggup dan sempat memberi pampasan perang kepada negara-negara yang pernah didudukinya, seperti Indonesia, yang waktu itu menerima sekitar 224-juta dolar Amerika, dan dana ini kemudian dimanfaatkan, antara lain untuk keperluan pembangunan sarana Asian Games 1962 di Jakarta, di mana nama Indonesia sempat harum semerbak berkat jasa medali emas (manusia terkencang di Asia) pelari kilat 100 meter putra Muhammad Sarengat, yang kemudian berprofesi sebagai dokter.
 Apa pun, bagi yang pernah mengalami dan merasakan kekejaman bala tentara Jepang ketika menduduki Indonesia di awal tahun 1940-an, rasanya sekali-kali tidak akan percaya kalau disampaikan kepada mereka betapa sopan dan santunya orang Jepang, paling tidak di Jepang sendiri.
Apa pun, bagi yang pernah mengalami dan merasakan kekejaman bala tentara Jepang ketika menduduki Indonesia di awal tahun 1940-an, rasanya sekali-kali tidak akan percaya kalau disampaikan kepada mereka betapa sopan dan santunya orang Jepang, paling tidak di Jepang sendiri.
“Kok bisa?”
Itulah peperangan yang mampu membrutalisasi manusia.
Mungkin itulah yang dimaksud pribahasa Jepang yang menjadi judul tulisan ini:
*jyaku niku kyō shoku*
Yang artinya:
“Jaku” artinya “lemah,” “niku” artinya “daging,” “kyo” artinya “kuat” “shoku” artinya “makan,”
Kasarnya bermakna:
“Yang lemah menjadi makanan yang kuat” – survival of the fittest!
Sayonara. Goodbye. (Bersambung)
Teks dan foto: Nuim Khaiyat